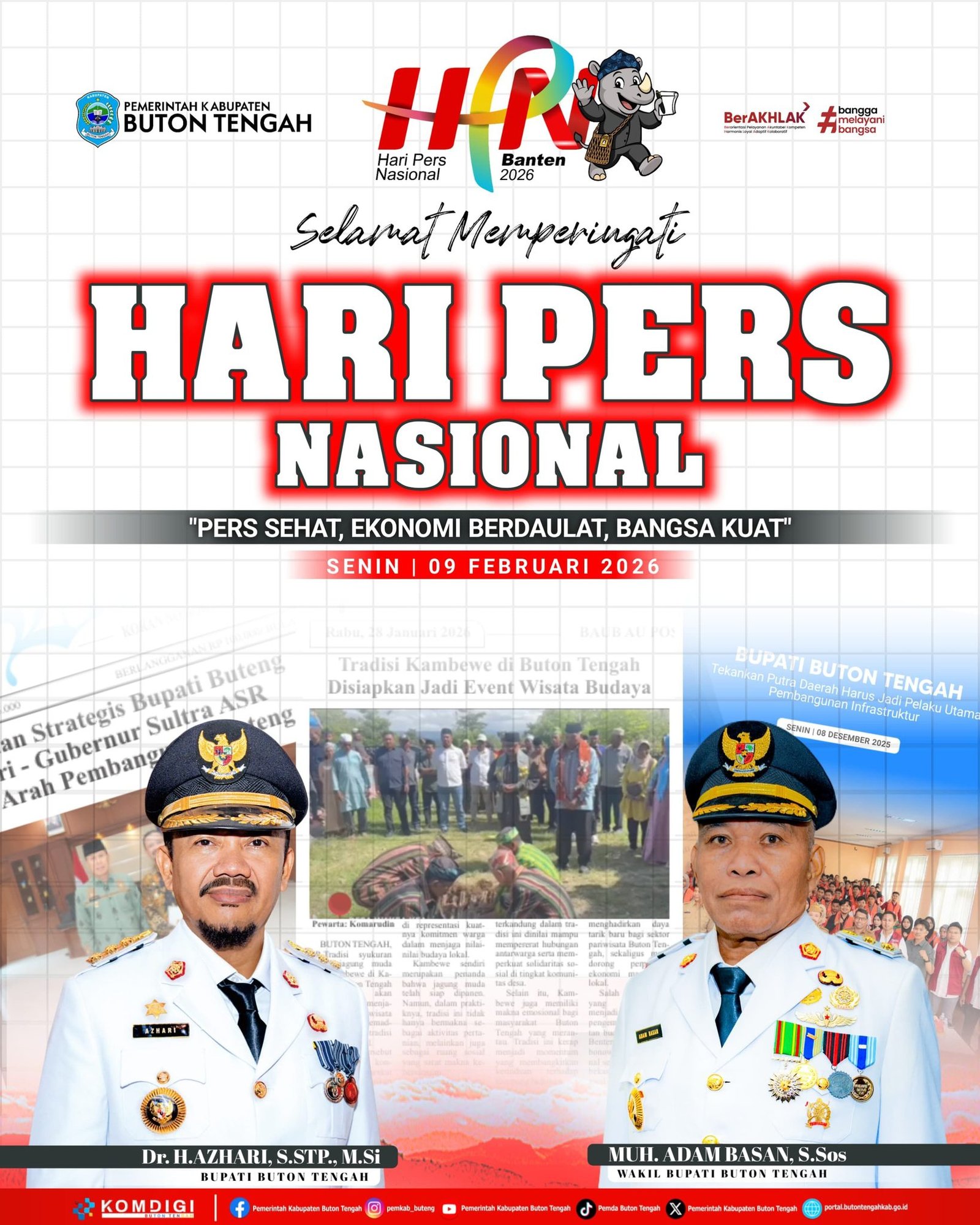Hibata.id – Di tengah hamparan sawah yang retak dan menguning sebelum waktunya, sekelompok petani di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, Pohuwato, Gorontalo, menyusun rencana yang tak biasa. Bukan menyewa alat berat, bukan lagi menunggu janji bantuan bibit, apalagi mengajukan proposal ke dinas. Kali ini, mereka memilih menempuh jalur yang lebih tua dari negara: Dayango.
Dayango adalah upacara spiritual yang diwariskan leluhur masyarakat Gorontalo. Sebuah ritual lintas dunia, tempat manusia memanggil arwah penjaga tanah agar bicara tentang apa yang tak bisa dijelaskan. Bagi para petani yang empat musim berturut-turut gagal panen, Dayango bukan pelarian, tapi jalan keluar terakhir.
“Kalau akal manusia sudah tak sanggup, kami panggil yang lebih tahu,” kata Manan, petani yang ikut menggagas ide ini.
Empat musim tanam, empat kali gagal panen. Tak ada cukup kata untuk menggambarkan derita mereka. Di musim pertama, para petani masih bisa menutup kerugian dengan hasil kopra dan pinjaman tengkulak.
Musim kedua, air irigasi mulai tersendat, lumpur menumpuk di saluran, tapi masih ada harapan. Memasuki musim ketiga, padi tumbuh kurus dan pendek, banyak yang mati sebelum sempat disabit. Dan kini, di musim keempat, hampir tak ada benih yang kembali.
“Sawah kami seperti dikutuk,” ujar Manan, separuh bertanya, separuh menyerah.
Petani lain menyebut air irigasi yang diduga tercemar. Ada pula yang mencurigai limbah dari aktivitas pertambangan di hulu. Tapi semua itu tak lebih dari bisik-bisik, karena tak satu pun pejabat datang membawa jawaban pasti.
Setiap kali para petani mengadu ke pemerintah, yang datang hanya rapat-rapat panjang, tanpa alat berat dan tanpa pengerukan saluran air. “Janji tuntas, tapi lumpur tetap di situ,” kata mereka.
Sementara itu, alat potong rusak, pupuk langka, asuransi tak mencair karena pengajuan selalu dianggap “terlambat”. Para tengkulak pun berhenti meminjamkan modal. Sistem pendukung yang dulu menopang ekonomi tani kini keropos satu per satu.
Di tengah kegamangan itu, muncul satu suara di forum rapat kelompok tani: bagaimana kalau kita gelar Dayango? Suara itu pelan, nyaris kalah oleh dengung kipas angin dan keluh kesah yang tak kunjung habis. Tapi ide itu diamini, bukan karena semua sepakat soal spiritualitas, tapi karena semua tahu: akal sehat tak lagi cukup menyelamatkan mereka.
“Ini bukan soal mistik,” kata seorang petani yang ikut hadir. “Ini soal kepercayaan. Kalau pemerintah tak bisa buka jalan, biar leluhur yang tunjukkan.”
Dayango, dalam tradisi Gorontalo, adalah ritual pemanggilan makhluk halus atau arwah penjaga tanah. Di masa lalu, upacara ini digelar untuk meminta petunjuk jika hasil panen tak wajar, jika desa diganggu musibah berkepanjangan, atau jika masyarakat percaya ada sesuatu yang “tidak terlihat” mengganggu tatanan hidup.
Bagi orang luar, Dayango mungkin dianggap tak rasional. Tapi bagi petani yang hidupnya terkubur lumpur irigasi dan tengkulak yang hengkang, rasionalitas bukan lagi soal logika—melainkan soal bertahan hidup.
Petani bernama Marwan Olii, pemilik 50 hektare lahan sawah, menyebut Dayango sebagai “doa yang keras.” Karena jika lewat protes tak ada yang dengar, mungkin lewat upacara mereka bisa bicara dengan yang lebih tinggi.
“Kami sudah ke camat, ke dinas, ke DPRD. Tapi semua hanya jawab dengan kasihan,” katanya. “Sekarang kami bicara ke langit.”
Ritual Dayango bukan hanya soal mistik. Ia juga simbol. Teriakan yang tak digubris di ruang formal, kini diganti dengan suara genderang, kemenyan, dan doa malam. Pemerintah boleh anggap ini sebagai bentuk keputusasaan, tapi di tanah tempat nasi tak lagi bisa tumbuh, doa adalah satu-satunya benih yang masih bisa ditanam.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait rencana Dayango massal ini. Tak ada tanggapan soal irigasi yang tak pernah tuntas dibersihkan, tak ada juga jaminan soal musim tanam berikutnya. Para petani tetap digiring ke sabar—tanpa disediakan harapan.
Maka mereka menempuh jalan lain. Jalan sunyi yang berakar dari sejarah dan keyakinan. Jalan yang tidak dicatat dalam buku strategi pembangunan, tapi hidup dalam tubuh dan ingatan orang-orang yang bersentuhan langsung dengan tanah.
“Kalau lewat Dayango, nanti ketahuan apa yang sebenarnya mengganggu kami,” ujar seorang perwakilan petani. “Kalau ini kutukan, biar dibuka. Kalau ini salah kelola, biar kelihatan siapa yang salah.”
Ketika negara tak lagi hadir di tengah penderitaan rakyatnya, warga akan menciptakan jalannya sendiri. Dan di Pohuwato, jalan itu bernama Dayango.